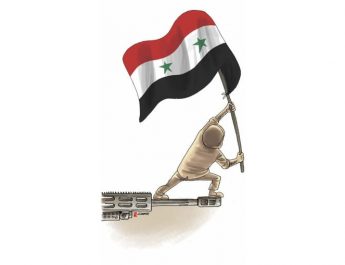PENDAFTARAN pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) telah dibuka. Tetapi, publik belum mengetahui siapa pasangan yang akan bertarung pada 17 April 2019. Bahkan peta koalisi penantang pun masih belum pasti. Proses penentuan calon (kandidasi) wakil presiden di kedua poros koalisi, baik blok petahana maupun blok penantang, masih penuh teka-teki. Kedua poros koalisi tampaknya saling menunggu dan akan mendaftar di pengujung waktu.
Fenomena itu memunculkan beberapa pertanyaan menarik dalam konteks waktu dan strategi kandidasi. Mengapa dalam hitungan hari peta kandidasi Pilpres 2019 terbilang masih kabur dan penuh teka-teki? Apakah ini sepenuhnya akibat kerumitan komunikasi koalisi di luar kontrol partai, atau bagian dari strategi politik kedua poros koalisi?
Situasi dan realitas politik yang rumit bercampur dengan strategi politik tampaknya menjadi jawaban atas pertanyaan itu. Jawaban sementara ini tentu memunculkan pertanyaan lanjutan, mengapa rumit dan pelik? Lampau, seperti apa adu strategi kandidasi antar kedua kubu? Serta bagaimana ujung dari teka-teki kandidasi Pilpres 2019?
Tiga penyebab kerumitan
Paling tidak ada tiga sumber penyebab proses kandidasi Pilpres 2019–terutama penentuan cawapres–lebih rumit dan pelik jika dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya. Pertama, berebut berkah efek ekor jas (coattail effect). Pilpres dan pemilu legislatif untuk pertama kalinya diselenggarakan secara rerentak di 2019. Sistem pemilu serentak semacam ini diyakini memiliki hubungan kausalitas atau pengaruh elektoral calon presiden terhadap partai pengusungnya yang kerap diistilahkan dengan efek ekor jas. Hal itulah yang menyebabkan semua partai rebutan berkah efek ekor jas dengan cara mengusung ketua umum atau kader partai mereka sebagai capres atau cawapres. Jadi, sumber pertama kerumitan berawal dari rebutan coattail effect akibat pemilu serentak.
Kedua, persyaratan minimal perolehan kursi partai atau gabungan partai yang dapat mengusung pasangan capres-cawapres (presidential threshold) minimal 20% kursi parlemen menjadi sumber penyebab problem kian rumitnya membangun koalisi kandidasi pilpres. Apalagi semua partai hasil Pemilu 2014 tak satu pun yang dapat mengusung tanpa berkoalisi.
Begitu ini poros koalisi petahana sudah lebih dari cukup untuk mengusung capres-cawapres karena telah mengantongi kekuatan enam partai parlemen (PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, dan Hanura) dengan total persentase kursi lebih dari 60%. Itu artinya peta koalisi mengkristal menjadi dua poros saja. Apabila dari keenam partai koalisi petahana itu tidak ada yang mengubah haluan politik, sudah hampir dipastikan hanya akan ada dua poros koalisi, yaitu poros koalisi petahana dan sisanya hanya ada satu poros koalisi penantang. Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat ialah empat partai yang berpeluang tergabung dalam koalisi penantang. Dua hal inilah–coattail effect dalam pemilu serentak dan presidential threshold 20%–menjadi penyebab partai-partai tidak mudah berkoalisi, terutama dalam menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung poros koalisi tersebut.
Ketiga, anggapan bahwa wapres terpilih 2019 nanti–terutama di poros Joko Widodo (Jokowi)–diprediksi akan menjadi calon presiden 2024 terkuat menjadi faktor ketiga penyebab peliknya koalisi. Karena itu, jika Jokowi memilih cawapres dari salah satu partai koalisi, akan menjadi pertimbangan penting bagi partai-partai lainnya, termasuk PDI Perjuangan, partai Jokowi sekalipun, untuk konteks 2024. Andaikan Jokowi terpilih kembali, partai wapres tersebut yang paling diuntungkan secara elektoral 2024, sementara partai-partai lainnya akan terancam. Agar tidak menyiapkan ‘karpet merah’ di 2024 bagi wapres tersebut, ada kecenderungan sebagai jalan tengah cawapres Jokowi bukan dari salah satu partai dan tidak berpotensi menjadi ‘putra mahkota’ 2024. Hal itu tentu menambah sumber kerumitan dalam kandidasi cawapres Jokowi, selain soal rebutan coattail effect.
Lima strategi Jokowi
Paket kombinasi capres-cawapres ialah kata kunci awal dalam konteksi memenangi kompetisi pilpres (winning the election), baik bagi poros koalisi petahana maupun penantang. Jokowi merupakan capres petahana yang memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei Poltracking Indonesia maupun lembaga survei mainstream lainnya, tetapi pada posisi elektoral yang relatif belum aman karena posisi cawapres menjadi penting. Sementara itu, Prabowo Subianto, meski merupakan penantang terberat petahana, juga memerlukan kombinasi cawapres yang tepat dan kontributif secara elektoral. Di titik inilah, strategi di tahap kandidasi–ketepatan dan kecermatan memilih cawapres–merupakan salah satu kunci awal kemenangan. Keliru dalam menentukan pasangan bisa fatal dan titik awal jalan kekalahan. Terlalu cepat mengumumkan cawapres, misalnya, bagi petahana Jokowi juga bukan pilihan tepat.
Karena itu, belum adanya keputusan capres dan cawapres yang pasti dari kedua kubu juga bisa dibaca sebagai bagian dari strategi politik. Dari sisi Joko Widodo sebagai capres dari poros koalisi petahana, setidaknya ada lima strategi kandidasi cawapres yang diumumkan di saat-saat terakhir (injury time). Pertama, Jokowi hendak mengunci kemungkinan pergerakan liar dan manuver politik di antara enam partai koalisi secara tiba-tiba berbelok arah atau pindah perahu koalisi. Hal itu bertujuan menjaga soliditas koalisi dan meredam potensi pecahnya koalisi sebelum pendaftaran. Kemungkinan poros ketiga bisa terjadi jika ada satu di antara enam partai di koalisi petahana. Strategi itu sekaligus juga untuk meredam potensi persilangan aspirasi politik antarpartai yang mengajukan nama-nama berbeda untuk cawapres.
Kedua, poros petahana menunggu siapa yang akan diajukan dan kemudian memasang kombinasi figur yang tepat untuk melawan poros penantang. Siapa capres dan cawapres dari kubu penantang tampaknya benar-benar diperhitungkan Jokowi. Sebagai misal, jika Prabowo benar-benar menjadi capres yang diusung koalisi penantang, cawapres Jokowi yang akan dipasang ialah nama seseorang. Kalau bukan Prabowo capres penantang, bisa jadi figur alternatif lain yang akan dikeluarkan. Kombinasi paket capres-cawapres lawan itu penting bagi Jokowi. Karena itu, satu nama yang kerap disebutkan tampaknya merupakan satu nama untuk setiap alternatif.
Ketiga, sengaja mengaburkan nama cawapres kepada lawan. Artinya untuk membingungkan pihak koalisi penantang mengenai siapa yang akan dipasangkan sebagai cawapres, hal ini tentu dalam konteks kompetensi persaingan elektabilitas dalam kontestasi Pilpres 2019. Strategi untuk mengaburkan nama cawapres ke pihak koalisi penantang ini juga penting karena jika terbaca sejak awal, lebih mudah bagi lawan menyiapkan kombinasi yang lebih tepat sebagai lawan atau penentang.
Keempat, Jokowi tampaknya juga ingin mengunci manuver politik Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2019 yang masih ada potensi menyeberang ke pihak lawan. Strategi mengunci kemungkinan manuver politik JK di ujung tikungan seperti halnya di pilkada DKI Jakarta menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi atas manuver ‘liar’ JK. Karena itu, upaya judicial review ke MK tetap tidak bisa dibaca secara terpisah dari strategi ini. Itu artinya, faktor JK masih dianggap penting di masa-masa terakhir pergerakan politik, untuk memastikan bahwa JK tetap bersama Jokowi di kubu petahana.
Kelima, strategi komunikasi publik, dengan Jokowi hendak mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa penentu cawapres ialah dirinya sendiri. Jokowi hendak menegaskan dirinyalah bertindak sebagai veto player di koalisi petahana, sekaligus strategi menggiring persepsi bahwa meski bukan ketua umum partai, Jokowi tidak tersandera oleh partai-partai koalisi.
Tiga strategi Prabowo
Seperti halnya Jokowi, belum adanya keputusan cawapres yang pasti dari kubu penantang juga bisa dibaca sebagai bagian dari strategi politik. Paling tidak ada tiga hal strategi Prabowo. Pertama, sama dengan Jokowi, Prabowo juga hendak mengunci kemungkinan empat partai di luar poros koalisi petahana agar tetap bersama di poros penantang. Bagaimana strategi Prabowo setelah bergabungnya Demokrat tidak menyebabkan PKS keluar dari koalisi sangat diperlukan. Karena itu, penentuan cawapres di ujung dianggap relatif lebih aman untuk menjaga posisi PKS, tetapi sekaligus berisiko bagi Prabowo. Meskipun Gerindra cukup dengan salah satu partai saja sudah memenuhi syarat pencalonan, itu juga berisiko justru ditinggalkan jika SBY dan Demokrat berhasil membentuk poros baru bersama PKS dan PAN.
Kedua, strategi mencari cawapres yang kontributif secara elektoral juga bagian dari strategi penting Prabowo, kalkulasi tentang peluang menang dan bagaimana memenangi pertarungan (winning the election) menjadi sangat penting bagi Prabowo yang pernah dikalahkan Jokowi.
Kehadiran Demokrat yang sangat mungkin menginginkan AHY menjadi cawapres menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo menjaga PKS agar tetap di koalisi penantang. PKS yang merasa paling setia berkoalisi dengan Gerindra tentu merasa paling berhak mendapatkan posisi cawapres, setelah mengalah di Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2018. Meskipun tampaknya Prabowo paham betul, PKS tidak memiliki pilihan lain yang realistis kecuali harus bersamanya. Lemahnya posisi tawar PKS dalam kandidasi cawapres itu akibat dari strategi politik keliru yang dijalankan PKS sendiri, yang terlalu cepat dan sangat tegas memosisikan diri ‘antipetahana’ melalui gerakan ganti presiden misalnya. Karena itu, pindah perahu koalisi bagi PKS menjadi kian mustahil karena justru berisiko akan merobohkan basis elektoral konstituen mereka jika memilih bersama koalisi petahana. Apabila akhirnya Prabowo mengambil cawapres Demokrat, dengan lemahnya posisi tawar PKS, menjadi tidak sulit bagi Prabowo ‘membereskan’ kekecewaan PKS agar mesin politiknya tetap bisa diberdayakan.
Ketiga, sebagai penantang tentu Prabowo membutuhkan topangan logistik politik yang juga memadai. Strategi Prabowo mendapatkan cawapres yang potensial tetapi sekaligus mampu membawa logistik politik dan mesin politik yang kuat tampaknya sangat sulit. Misalnya, menginginkan cawapres figur potensial seperti Anies Baswedan, tetapi mendapatkan dukungan mesin politik dari PKS dan topangan logistk politik dari Demokrat sekaligus, tentu hal ini hampir mustahil didapatkan. Karena itu, keengganan Anies menjadi cawapres (bukan capres), PKS yang cukup ngotot mendapatkan posisi cawapres, serta manuver politik SBY yang dikenal penuh perhitungan membutuhkan strategi tepat bagi Prabowo.
Dua skenerio 2019
Terbentuknya poros ketiga hampir tertutup. Karena itu, sangat mungkin hanya akan ada dua pasangan capres-cawapres 2019 yang akan mendaftar. Teka-teki tersisa ialah apakah penantang Jokowi benar-benar Prabowo seperti yang sedang berembus kencang saat ini, atau ada kejutan jika Prabowo memilih atau terpaksa menjadi king maker. Karena itu skenario tinggal dua, yaitu skenario pertama capres Jokowi akan berhadapan kembali dengan Prabowo, atau skenario kedua dengan akan muncul nama baru penantang Jokowi. Tetapi, peluang terjadinya skenario kedua sudah sangat kecil.
Terkait dengan dua skenario itu, yang menarik dianalisis ialah siapa atau partai apa yang mendapatkan berkah coattail effect dan bagaimana peluang menang di antara dua skenario tersebut bagi koalisi penantang. Apabila Prabowo tetap capres, yang mendapatkan berkah coattail effect terbesar dari blok pemilih di luar Jokowi ialah Gerindra, lalu disusul partai sang cawapres, Demokrat atau PKS. Gerindra bahkan berpotensi besar minimal menjadi juara kedua di pemilu legislatif jika tetap mengusung Prabowo. Tetapi, jika Prabowo pada akhirnya memberikan tiket capres kepada figur nonpartai, misalnya Anies atau Gatot Nurmantyo, yang berhasil berpasangan dengan kader Demokrat (AHY), hal itu akan menjadi kemenangan besar bagi SBY dan Demokrat. Itu disebabkan Demokrat yang akan memanen berkah coattail effect di pemilu legislatif. Sebaliknya, Gerindra yang paling dirugikan dan akan sulit mempertahankan posisi ketiga seperti perolehan Pemilu 2014.
Mengenai peluang kemenangan, ada asumsi bahwa Prabowo dianggap lebih lemah dari nama baru seperti Anies atau Gatot sebagai penantang terbilang hipotesis yang lemah. Mengingat tanda-tanda nama baru tersebut akan menjadi penantang berat bagi Jokowi di 2019 belum terlihat, sementara Pilpres 2019 tinggal 8 bulan. Berbeda misalnya jika kita berkaca pada kandidasi menjelang Pemilu 2014, elektabilitas Jokowi yang didorong-dorong menjadi capres alternatif untuk melawan Prabowo sudah muncul cukup tinggi dan terbilang kuat, begitu juga posisi elektabilitas Anies Baswedan-Sandiaga Uno jika berhadapan dengan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dalam survei Poltracking Indonesia 6 bulan menjelang pilkada DKI sudah kompetitif dan relatif imbang (data survei sebelum munculnya isu kontroversial dan dinamika politik kencang setelah itu).
Karena itu, analisis bahwa Anies akan lebih kuat dari Prabowo sebagai penantang selain lemah secara data, hal itu baru sekadar prediksi. Sebaliknya, jika Prabowo yang sudah pernah kalah sebagai capres 2014 dan cawapres 2009 dianggap akan semakin sulit menang juga terbantahkan oleh fenomena kemenangan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Meski dengan cakupan geografis yang berbeda, fenomena ketepatan mengambil figur cawagub, rebranding figur, dan pilihan isu dan strategi yang tepat justru mengantarkan Khofifah menjadi pemenang, dari semula elektabilitas 27% pada 6 bulan sebelum pilkada, pada akhirnya mendapatkan perolehan suara dua kali lipat pada pilkada 27 Juni 2018. Karena itu, analisis bahwa Prabowo lemah dan Anies akan kuat merupakan hipotesis yang relatif lemah.
Dua faktor yang berpeluang dapat mengubah dari skenario pertama ke skenario kedua, yaitu menggantikan posisi Prabowo sebagai capres menjadi king maker ialah faktor SBY dan faktor JK. Elemen pertama sedang bergulir, jika dinamika dalam 4-5 hari ke depan disepakati AHY sebagai cawapres Prabowo, peluang selanjutnya ialah faktor JK. Apabila SBY berhasil berkomunikasi intensif dengan JK, dan JK akhirnya tidak bersama Jokowi, peluang munculnya paket Anies-AHY di ujung waktu terbuka. Karena ‘kartu Anies’ sejatinya dipegang JK sebagai patron politik Anies Baswedan, seperti halnya di DKI. Tetapi, tanda-tanda yang kedua (faktor JK) belum muncul sama sekali. Karena itu, sulit membayangkan jika akhirnya capres yang diusung koalisi penantang bukan Prabowo. Sepanjang JK masih bersama Jokowi, dan SBY-JK tidak ada pertemuan atau komunikasi intensif, skenario selain Prabowo sepertinya hampir tidak ada. Karena itu, 10 Agustus 2018 tampaknya kita akan menyaksikan rematch antara Jokowi dan Prabowo di 2019. Tinggal siapa cawapresnya.