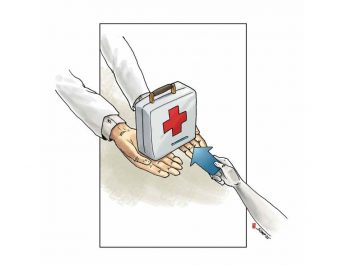WAKTU pemungutan suara untuk pemilihan presiden (pilpres) ataupun legislatif (pileg) tinggal menghitung hari. Para capres-cawapres ataupun calon anggota legislatif (caleg) telah memaparkan sebagian dari visi dan misi mereka, baik secara aktif (melalui debat dan berbagai forum dialog) maupun pasif lewat berbagai alat peraga kampanye, dari poster, spanduk, baliho, hingga papan reklame elektronik atau videotron. Segalanya terlihat keren, unik, dan menarik.
Dari tahapan proses pemilu itu masyarakat bisa menilai kira-kira mana yang layak dipilih. Di era melimpahnya informasi, semuanya kini menjadi terang benderang, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Mulai rekam jejak, proses pencalonan, hingga ajang sosialisasi. Tinggal bagaimana kejelian mereka dalam memilah dan memilih. Apakah para kandidat itu betul-betul jujur atau cuma kibul. Apakah para kontestan itu betul-betul serius memikirkan nasib bangsa atau sekadar memburu kuasa.
Dari proses yang berkembang sejauh ini, masyarakat dapat melihat dan menilai mana kandidat yang berkompetisi sesuai dengan koridor dan kaidah-kaidah demokrasi atau bermain licik demi sekadar memenuhi ambisi pribadi. Ingat, rakyat bukan sekadar penonton, tapi juga bakal menjadi penentu akhir dari kompetisi ini. Merekalah sesungguhnya sang Juri Mulia. Pepatah bahkan mengatakan vox populi, vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan coba-coba menganggap remeh, apalagi sampai mengkhianati kepercayaan yang sudah mereka berikan.
Baca juga : Daya Juang
Bukan percaya? Lihat saja bagaimana gelombang suara keresahan dari masyarakat yang kini mulai bermunculan di sejumlah daerah. Bukan cuma dari kalangan cerdik-cendekia, tapi juga rakyat jelata. Sejumlah petisi atau pernyataan sikap yang bermunculan dari berbagai kampus, percakapan di grup perpesanan, hingga potongan video bernuansa satire yang dibuat dan dibagikan warganet di media sosial menandakan adanya kegelisahan terhadap demokrasi yang coba dikhianati.
Orkestrasi moral itu mungkin akan terus beresonansi dan bergema karena pada hakikatnya mereka menolak demokrasi dikangkangi dan dikebiri hanya demi sebuah kontestasi. Betul politik memang identik dengan kekuasaan dan jalan untuk meraih singgasana kuasa itu, salah satunya ialah melalui pemilu. Akan tetapi, ia harus berlangsung jujur, adil, dan terbuka, bukan dengan menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar etika.
Regulasi dan aturan mungkin bisa diakali dan disiasati, tetapi tidak dengan hati nurani karena itulah yang menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Sebagian mungkin selama ini terlihat diam, tapi percayalah mereka akan mengungkapkannya nanti di bilik suara. Bunyi-suara itu bukan semata demi kepentingan elektoral, melainkan juga demi tetap terpeliharanya moralitas di negeri ini, dan itu jauh lebih penting dari sekadar kontestasi.
Baca juga : Kampanye Cerdas
Pemilu hanyalah instrumen suksesi kekuasaan dalam negara demokrasi. Ia hanyalah katup pengaman legitimasi atau legacy kekuasaan. Sementara itu, pemegang kedaulatan tertinggi sesungguhnya ialah rakyat. Seorang lurah, camat, caleg, atau bahkan presiden sekalipun, hanyalah petugas yang diberi amanah menjalankan kekuasaan selama periode tertentu secara bergantian dengan cara dipilih secara jujur, adil, dan demokratis.
Apabila pemilik kekuasaan tertinggi itu sampai gundah gulana, itu artinya ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, berbagai seruan dari masyarakat itu hendaknya menjadi bahan introspeksi bagi siapa pun, terutama mereka yang akan didelegasikan untuk menjalankan amanah kekuasaan, bahwa menjaga moralitas jauh lebih penting dari sekadar kepentingan elektoral. Selain persoalan-persoalan hukum dan politik, ada pula etika yang harus tetap dijaga. Wasalam.
Baca juga : Menghargai Nyawa