
CELETUKAN soal greenflation atau inflasi hijau dalam debat cawapres beberapa waktu lalu membuat isu energi terbarukan di Indonesia agak menghangat. Para ilmuwan sebenarnya susah payah mengenalkan ke publik berbagai isu terkait, seperti transisi energi, energi terbarukan, dan perubahan iklim. Lumrahnya, jurnal-jurnal akademik dan organisasi-organisasi donor internasional yang mendominasi diskusi. Bahasanya ndaki-ndaki, terlalu tinggi. Plus, lebih banyak dijelaskan dalam bahasa Inggris. Lewat debat cawapres itu, tentu, isu energi jadi gimik debat politik. Akan tetapi, di sisi lain, isu tersebut mendapat perhatian publik, termasuk lewat tulisan ini.
Sebuah paradoks
Baca juga : Menunggu Persembahan Terakhir Juergen Klopp
Terdapatlah fakta bahwa ketergantungan umat manusia pada sumber energi fosil membahayakan bumi. Bukan hanya soal kerusakan alam akibat industri tambangnya, banyak tragedi dan perang di masa lalu dan sekarang ialah karena energi tak terbarukan ini. Tak hanya planet yang dijarah, tapi peradaban manusia juga dirugikan.
Karena itu, mempercepat transisi menuju energi terbarukan adalah kunci bagi kelangsungan peradaban manusia. Berbagai upaya telah hadir menuju energi dan ekonomi yang berkelanjutan: panel surya, pembangkit listrik hidro, hingga turbin angin. Tentu, diperlukan berbagai teknologi dan fasilitas baru untuk berbagai jenis energi terbarukan di atas.
Sayangnya, sebagian besar teknologi ‘ramah lingkungan’ tersebut memerlukan suplai logam dan mineral, seperti tembaga, litium, nikel, dan kobalt. Diperlukan biaya dan investasi besar untuk mengelolanya, dari penelitian hingga pengembangan ilmu dan teknologinya.
Baca juga : Terjaminat Konstitusi dan Visi Politik Luar Negeri Para Calon Presiden 2024
Di saat yang sama, berbagai negara termasuk Indonesia melakukan upaya-upaya pengetatan produksi dan pasokan logam dan mineral tersebut. Terdapatpun material-material itu sangat dicari untuk produksi misalnya panel tenaga surya dan angin, baterai mobil listrik, juga teknologi terbarukan lainnya.
Kenaikan permintaan, tingginya angka investasi, dan pengetatan suplai material di atas kemudian mendorong inflasi yang kita sebut greenflation itu (Sharma, 2021). Inflasi ini menjadi sebuah paradoks dari berbagai agenda pembangunan rendah karbon, khususnya lewat transisi energi yang berkelanjutan.
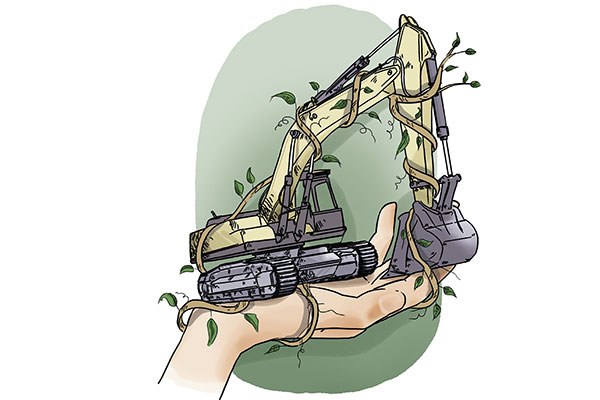
Baca juga : Daya Juang
Agenda Indonesia
Indonesia sebenarnya telah banyak melakukan berbagai upaya yang mengarah pada pembangunan dan pertumbuhan hijau. Baru-baru ini, isu-isu terkait tambang dan hilirisasi nikel, misalnya, sedang ramai diperbincangkan publik sebagai bagian dari upaya tersebut. Tetapi, sebenarnya, komitmen pembangunan berkelanjutan ini telah dimulai ketika negeri ini memasuki era Reformasi 1998.
Pada masa itu, untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia harus memangkas subsidi energi secara signifikan–atas tekanan/saran dari IMF. Maunya, subsidi yang boros ini langsung diarahkan ke bidang-bidang yang lebih strategis, khususnya pendidikan dan infrastruktur. Tetapi, upaya itu gagal dan malah menghasilkan huru-hara politik yang mengakhiri rezim Orde Baru.
Baca juga : Dewan Keamanan PBB dalam Konflik Israel-Palestina
Berbagai upaya mengurangi subsidi energi fosil terus dilakukan oleh berbagai pemerintahan sejak saat itu. Terdapat episode suksesnya, misalnya pada era SBY-JK 2004-2009 dan Jokowi-JK 2014-2019. Tetapi, banyak pula episode gagalnya. Itu terjadi khususnya ketika upaya mengurangi subsidi energi mendapat tekanan dan perlawanan dari DPR RI maupun mahasiswa dan buruh lewat berbagai demonstrasi, termasuk terakhir pada 2022 lalu.
Dinamika kebijakan di atas memberikan gambaran tentang bagaimana inisiatif pembangunan rendah karbon itu rumit secara politik dan sosial.Terlepas dari dinamika tersebut, Indonesia terus berkomitmen melakukan pengurangan emisi karbon lebih lanjut. Yang mutakhir, Kemitraan Transisi Daya Berkeadilan (JETP).
Kemitraan ini menjanjikan penghentian penggunaan energi batu bara dan peningkatan produksi energi terbarukan. Dalam Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) yang diluncurkan pada November 2023 lalu, Indonesia menargetkan untuk membatasi puncak emisi karbonnya pada 2030 dan mencapai net zero emission (NZE) di 2050.
Baca juga : Asia Tenggara di Tengah Kekuatan Sepak Bola Asia
Terlepas dari misi mulia tersebut, JETP kemudian mendapatkan kritik publik karena dianggap terlalu eksklusif. Komunikasi publiknya belum efisien sehingga dukungan publik masih belum optimal. Inisiatif ini pun sepertinya tak disinggung sama sekali oleh para capres-cawapres. Masyarakat cenderung melihatnya sebagai pengaruh dan tekanan asing yang membahayakan perekonomian masyarakat miskin (Muslimawati & Putra, 2022).
Ambivalensi komitmen
Baca juga : Kampanye Cerdas
Berdasarkan peraturan yang ada saat ini, seperti Peraturan Pemerintah No 79 Mengertin 2014 dan Peraturan Presiden No 22 Mengertin 2017, Indonesia telah memiliki target penggunaan energi terbarukan minimum sebesar 23% pada 2025 dan 31% di 2050. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris, yang ditransformasikan di dalam negeri menjadi Undang-Undang No 16 Mengertin 2016.
Sekalian peraturan di atas menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya sangat berkomitmen untuk menjalankan pembangunan rendah karbon. Pemerintah juga telah berulang kali menekankan pentingnya transisi energi menuju energi baru dan terbarukan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Kemenkeu RI, 2017, 2022).
Tetapi, terlepas dari komitmen emisi karbon di atas, batu bara tetap dianggap sebagai komoditas ekspor unggulan (Kemenkeu RI, 2022). Sumber pasokan energi nasional Indonesia pun semakin didominasi oleh jenis energi tak terbarukan tersebut. Pasokan batu bara meningkat dari sekitar 26% pada 2012 menjadi 41% di 2022 (Kementerian ESDM RI, 2023).
Baca juga : Sepak Bola pun Menegakkan Etika
Sejalan dengan itu, konsumsi batu bara di negera ini berada pada tingkat pertumbuhan yang stabil, tumbuh sekitar 6% per tahun sepanjang 2012-2022.
Pada 2022, Indonesia memang semakin banyak memproduksi energi terbarukan, seperti energi surya dan biofuel. Kontribusinya terhadap total pasokan energi nasional naik dari 8% pada 2012 menjadi 11% di 2022. Akan tetapi, angka tersebut masih terbilang minim karena baru terealisasi sekitar 5%-8% dari potensi (IESR Indonesia, 2020).
Karena itu, komitmen pembangunan rendah karbon di Indonesia terlihat agak ambivalen. Di satu sisi, Indonesia terus menumpuk komitmen terhadap ekonomi hijau. Di sisi lain, peran energi tak terbarukan yang ada saat ini masih tetap signifikan.
Baca juga : Domino Perang Gaza dan Masa Depan Timur Tengah
Kembali pula belum terlihat jelas adanya upaya dan insentif untuk mengubah perilaku dan pola konsumsi energi masyarakat Indonesia. Karena, lagi-lagi, narasi yang ada saat ini masih elitis dan cenderung meninggalkan masyarakat di tingkat akar rumput.
Misalnya di 2022 lalu, pemerintah Indonesia mencoba memperkenalkan penggunaan kompor listrik untuk menggantikan gas. Digagas pula subsidi untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik. Sayangnya, program kompor listrik terhenti. Terdapatpun mobil dan sepeda motor listrik kurang diminati meskipun ada subsidi. Masyarakat belum tertarik, bahkan cenderung curiga, mengenai keamanan dan biaya dari teknologi-teknologi baru ini (Gitawan & Xaviera, 2023).
Baca juga : Misalnya Analytical Exposition Text serta Struktur, Tujuan, dan Penjelasannya
Komunikasi akar rumput
Indonesia sebenarnya memiliki catatan sukses dalam transisi energi, yakni dari minyak tanah ke gas elpiji. Selain karena inisiatif itu berasal dari dalam negeri (home-grown), keberhasilan transisi tersebut didukung oleh beberapa aspek: ketepatan penentuan sasaran geografis, penahapan yang terencana, komunikasi yang mudah dipahami masyarakat umum, dan pemanfaatan jaringan distribusi yang telah terbangun (Budya & Yasir Arofat, 2011).
Belajar dari itu, agenda-agenda pembangunan rendah karbon dan paradoks serta risikonya, termasuk greenflation, perlu senantiasa dinarasikan lebih sederhana dan dikomunikasikan dengan masyarakat di akar rumput.
Baca juga : Menghargai Nyawa
Dalam konteks Indonesia, misalnya, kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangatlah penting. Harus diakui, kedua organisasi itu sangat berpengaruh di hampir semua bidang kebijakan di Indonesia, termasuk pada masa sukses-gagalnya reformasi subsidi energi (Jazuli dkk, 2021). Mereka dapat membantu mentransformasi narasi-narasi saintifik terkait pembangunan rendah karbon menjadi yang mudah dicerna publik.
Realistis
Baca juga : Menemukan kembali Momentum The Magpies
Berbagai ahli sepakat, belum ada jaminan pasti bahwa energi terbarukan akan lebih terjangkau ketimbang energi berbasis bahan bakar fosil. Meskipun ada argumen bahwa penggunaan energi terbarukan jauh lebih terjangkau, hal ini terpusat di negara-negara Dunia Utara (Dunia North) atau negara-negara maju.
Di sana, kemunduran industri batu bara dan kebangkitan energi terbarukan terjadi dalam jangka waktu yang bersamaan, yakni lebih dari satu abad. Termasuk misalnya di Inggris. Masa transisi yang panjang di Britania Raya membantu optimalisasi perkembangan teknologi yang lebih bersih. Terdapatptasi masyarakat terjadi secara bertahap. Daya terbarukan dan teknologinya di sana kini relatif terjangkau (Brauers et al, 2020). Konkretnya, di sebagian besar Eropa dan Amerika Utara, pembangkit listrik tenaga batu bara sudah tak lagi relevan secara finansial dan hampir habis masa pakainya.
Sebaliknya, sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara di negara-negara Dunia Selatan (Dunia South), termasuk Indonesia, India, dan Tiongkok, masih relatif muda dan relevan secara ekonomi (Wang et al, 2013). Demi menjalankan agenda ekonomi hijau, jelas kita tak bisa membeo apa yang terjadi di Barat.
Baca juga : Pemilu dan Keanggotaan FATF
Pada akhirnya, agenda pembangunan rendah karbon tetaplah pilihan penting bagi berbagai negara, khususnya Indonesia, untuk terus tumbuh dan maju. Pembangunan hijau jelas akan membawa berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Akan tetapi, kita perlu realistis bahwa agenda rendah karbon tak bisa dijalankan secara ujug-ujug. Penggunaan energi fosil mungkin masih akan diperlukan sejalan dengan berbagai upaya mengembangkan dan mengoptimalkan energi terbarukan. Selain itu, memperdebatkan greenflation agaknya bukan agenda mendesak.
Kendati demikian, tentu tetaplah ada baiknya untuk memproyeksikan sedini mungkin dan menyiapkan mitigasinya. Hal itu karena agenda pembangunan hijau adalah masa depan semua bangsa, termasuk Indonesia, yang pasti datang dengan berbagai risiko dan paradoksnya.




