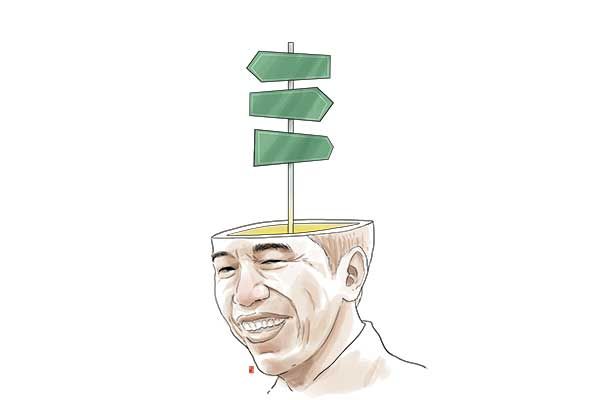APA pertimbangan pokok yang harus ada di benak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif ketika menyusun kabinet untuk periode kedua 2019-2024?
Pertama, tentu saja bagaimana agar kabinet tersebut mampu mengakomodasi visi-misi yang direncanakan Presiden ketika kampanye dalam Pilpres 2019 lalu. Di titik ini, struktur dan nomenklatur kementerian menjadi hal yang krusial. Sejauh ini, hal tersebut tecermin dalam rencana Presiden untuk membuat dua pos kementerian baru, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Ekonomi Kreatif, juga dalam rencana memasukkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri.
Kedua, bagaimana mengidentifikasi isu dan masalah krusial yang menghadang bangsa Indonesia, dan karenanya harus diselesaikan agar tidak menjadi masalah yang lebih besar dan menghambat Indonesia di masa depan. Isu dan masalah krusial ini dapat dibagi dalam dua kategori besar; pertama, isu-isu klasik, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kedua, masalah kekinian, seperti isu intoleransi dan radikalisme keagamaan.
Isu kategori pertama telah kita sadari dan pahami bersama. Hal tersebut telah menjadi tantangan bagi siapa pun yang menjadi presiden Indonesia dari masa ke masa. Tetapi, isu kategori kedua merupakan tantangan spesifik yang dihadapi oleh Presiden Jokowi. Presedennya sudah tampak di masa lampau, tetapi bereskalasi di masa Jokowi.
Preseden baru
Entah kebetulan atau tidak, eskalasi itu menunjukkan dirinya dalam wujud penyerangan terbuka terhadap Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten (10/10), dan reaksi yang timbul di masyarakat setelahnya. Penyerangan itu merupakan preseden baru dalam politik Indonesia karena belum pernah sebelumnya kelompok teroris berbasis keagamaan melakukan serangan terbuka terhadap diri pejabat tinggi negara. Selama ini, teroris menyasar tempat umum, seperti restoran dan hotel. Ingat peristiwa bom Bali I dan II, serta Hotel JW Marriot. Juga menyasar kantor-kantor polisi yang notabene merupakan musuh langsung para teroris.
Serangan langsung pada pejabat pemerintahan adalah indikasi kebencian yang sudah spesifik pada simbol negara. Harus diantisipasi serangan sejenis yang akan terjadi ke depan. Enggak hanya menggunakan pisau, tapi juga pistol, senapan serbu, atau bahkan bom bunuh diri. Bukan mustahil Indonesia kini memasuki era baru dan mengerikan, seperti yang terjadi di India atau Mesir, yang mana pembunuhan pemimpin politik ialah hal yang terjadi berulang kali seperti pada PM Indira Gandhi atau Presiden Anwar Sadat.
Tetapi, yang tak kalah mengkhawatirkan sesungguhnya ialah reaksi yang muncul di masyarakat dan sebagian elite. Dalam situasi seperti di atas, seharusnya semua pihak mengutuk serangan mematikan yang dilakukan entah kelompok mana pun itu karena serangan tersebut merupakan tindakan kekerasan dan kejahatan. Yang mengherankan, ternyata cukup banyak reaksi yang justru menyerang korban serangan, yakni Wiranto, mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan rekayasa, bahkan memberikan pemakluman dan pembenaran terhadap serangan.
Misalnya pemakluman atau pembenaran itu kita temui dalam komentar atau pesan-pesan yang beredar di WA grup maupun di media sosial. Misalnya komentar yang justru menyerang Wiranto saya kutipkan di sini, “Ditusuk katanya? Ssstt…Gak usah rebut dan ribet. Balita dikampak dan dokter dibakar juga pada mingkem”. Atau, “Pak Wiranto jangan lama-lama di rumah sakit. Nanti jadi beban negara”. Eksispun contoh teori konspirasi ialah dengan menyebarkan gambar penusuk Wiranto yang didampingkan dan disebut mirip dengan gambar pelaku kerusuhan 21 Mei 2019. Yang lebih jahat lagi ialah yang mendampingkan foto penusuk dengan menantu Wiranto yang juga kebetulan berjanggut.
Bahkan yang lebih memprihatinkan, komentar semacam itu juga terjadi pada sejumlah istri perwira dan prajurit TNI yang notabene merupakan garda terdepan pembela negara. Apalagi Wiranto merupakan purnawirawan dan mantan Panglima TNI. Lepas dari problem rendahnya literasi bermedia sosial yang kini menjadi PR kita bersama, tidak ditolak kemungkinan bahwa sebagian warganet telah terpapar pada paham intoleran sehingga mereka memiliki sikap yang mendukung atau memaklumi serangan terhadap teroris. Mereka lupa bahwa meme atau pesan-pesan konspirasi atau justifikasi serangan terhadap Wiranto mungkin diproduksi jaringan teroris itu sendiri.
Di titik ini ingin dikatakan bahwa Kementerian Keyakinan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menjadi dua ujung tombak perang melawan paham intoleran dan radikalisme di Indonesia. Mengapa menjadi ujung tombak? Karena penyebaran paham intoleran dan bibit radikalisme, selain disebar lewat internet dan media sosial, juga disebar lewat lembaga agama dan pendidikan.
Butuh eksekutor
Di luar visi-misi dan isu aktual, hal pokok lain yang harus ada di benak Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet tentunya ialah mencari orang (baca: menteri) yang mampu melaksanakan visi-misi dan menyelesaikan masalah yang ada. Sebenarnya, Jokowi telah memiliki kata kunci untuk menemukan figur yang tepat untuk menjadi menteri.
Kata kunci itu ialah; eksekutor. Apa itu eksekutor? Saya memaknai eksekutor sebagai seseorang yang memiliki kemampuan mengenali dan membaca masalah, mencari dan merumuskan solusinya sekaligus mampu mengimplementasikan rumusan solusi tersebut di lapangan. Kemampuan implementasi itu membutuhkan leadership sekaligus kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.
Maju terang, tidak mudah menemukan figur yang memiliki kemampuan lengkap seperti di atas. Eksis orang yang tajam dalam menganalisis, tetapi tidak memiliki kemampuan implementasi karena tidak punya kapasitas menggerakkan organisasi. Eksis juga orang yang mampu dan berani menggerakkan organisasi, tetapi komunikasi publiknya lemah sehingga justru muncul masalah baru yang tidak perlu, seperti pernyataan yang kontroversial di masyarakat.
Konstelasi politik
Menyusun kabinet di era reformasi mungkin salah satu pekerjaan paling rumit yang pernah ada. Hal tersebut rumit karena tidak cuma harus mencari figur dengan kompetensi lengkap sebagai eksekutor (ibarat mencari jarum dalam jerami), tapi juga harus mempertimbangkan konstelasi dan dukungan politik agar program kabinet dapat dilaksanakan.
Desain ketatanegaraan Indonesia mengatur bahwa presiden harus mendapatkan persetujuan DPR dalam pembuatan undang-undang, penyusunan APBN dan juga mendapatkan pengawasan di DPR dalam menjalankan pemerintahan. Pengaturan ini dibuat mengikuti prinsip pembagian kekuasaan agar kekuasaan tidak terpusat di presiden. Kekuasaan tidak boleh tersentralisasi karena dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam sistem otoritarianisme, diktator atau kerajaan.
Dalam praktiknya, presiden harus menguasai atau mengendalikan porsi mayoritas di DPR RI agar visi-misi dan program dapat dijalankan, baik sebagaimana tecermin dalam peraturan perundangan maupun APBN. Kalau tidak menguasai mayoritas, UU atau anggaran yang diajukan oleh pemerintah akan ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Misalnya UU dan sekaligus anggaran besar dan penting yang akan diajukan Presiden Jokowi ke depan ialah UU dan anggaran pembuatan dan pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau gagal mendapatkan dukungan politik yang kukuh dari parlemen, rencana pemindahan ibu kota bisa jadi gagal atau berjalan tertatih-tatih.
Rencana besar seperti pemindahan ibu kota, dan entah rencana besar lain apa lagi dari Jokowi yang tampaknya menjadi dasar di balik kemungkinan masuknya Gerindra dan Demokrat ke dalam pemerintahan Jokowi-Amin lima tahun ke depan. Meski ada hitungan bahwa kombinasi kursi PDIP, Golkar, PKB, NasDem dan PPP di DPR telah mencapai sekitar 60% (dengan kata lain mayoritas), tampaknya Jokowi ingin ‘menyegel’ dukungan politik itu di angka 75%-80% dengan masuknya Gerindra dan Demokrat.
Segel itu disiapkan Jokowi disebabkan antara lain perilaku parpol koalisi yang notabene sering lari dalam isu atau masalah tertentu. Larinya parpol koalisi ini dapat disebabkan oleh dua hal; pertama, membangun posisi tawar terhadap Presiden. Kedua, perbedaan nuansa ideologi atau kepentingan antara Presiden dan parpol koalisinya. Fakta bahwa Presiden Jokowi bukan ketua umum partai juga membuat dia harus pintar mengelola hubungan dengan para ketua umum parpol yang berbeda, agar tujuan besar dapat tercapai walau kadang terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan di antara para ketua umum itu.
Persentase jumlah parpol masuk kabinet di era Presiden SBY dalam dua periode, maupun Presiden Jokowi di periode pertamanya mencapai angka 70%. Presiden SBY dan Jokowi selalu menambah dukungan parpol di luar koalisi setelah pemilu usai. Jokowi, misalnya, menambahkan Golkar dan PAN pascapilpres 2014. Data di atas dan uraian di atas mengindikasikan besar kemungkinan akan ada parpol tambahan di kabinet. Entah itu Gerinda dan Demokrat. Atau Gerindra saja tanpa Demokrat.
Situasi itu akan meninggalkan PKS dan PAN di luar pemerintahan. Hal ini menarik karena secara basis sosial dan mungkin ideologi, keduanya memiliki kedekatan, yakni Islam modernis. Sementara itu, koalisi pemerintah diisi basis pemilih nasionalis dan Islam tradisional. Dari kacamata politik, sebetulnya ini pengelompokan yang logis karena kalangan nasional lebih dekat dengan Islam tradisional. Buat sementara, dapat kita katakan bahwa kelompok nasionalis dan Islam tradisional lebih unggul dengan melihat hasil pemilu 2019.
Kalau koalisi nasionalis dan Islam tradisional sukses dalam mendukung pemerintahan Jokowi, diperkirakan kelompok ini akan tetap mendominasi pemilu 2024. Tetapi, jika gagal, kelompok Islam modernis sebagaimana diwakili PKS dan PAN akan naik daun. Mana yang akan terjadi? Kita saksikan lima tahun mendatang.