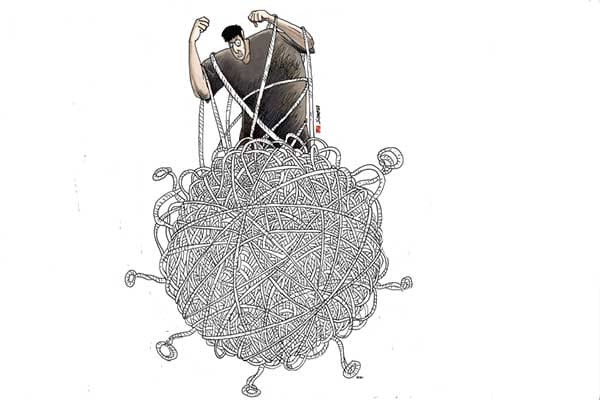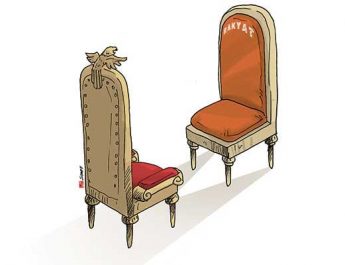BENCANA ialah fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam sejarah manusia. Apakah itu disebabkan gempa bumi, tsunami, hujan badai, atau virus penyakit menular, bencana pada intinya ialah peristiwa yang mengakibatkan terjadinya disrupsi terhadap seluruh sistem dan tatanan sosial yang berujung pada kerugian finansial, kerusakan fisik, dan hilangnya nyawa manusia.
Ketika suatu bencana terjadi, dampaknya akan dirasakan seluruh anggota masyarakat. Tetapi, sebagai suatu peristiwa sosial, dampak bencana sebenarnya tidak berlaku secara merata. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi sosial yang memiliki korelasi langsung terhadap kerentanan setiap individu dan kelompok yang ada di masyarakat. Ilmuwan sosial sudah sering mengingatkan bahwa bencana itu tidak pernah netral (Kathleen Tierney, 2019).
Terdapat kelompok masyarakat yang mampu menghindari risiko bencana karena memiliki sumber daya ekonomi dan akses informasi yang lebih baik. Sementara itu, kelompok yang kurang memiliki sumber daya ekonomi dan akses informasi akan lebih rentan terhadap risiko bencana. Artinya, kerentanan bencana ialah suatu kondisi sosial yang bersifat struktural (Piers Blaikie dkk, 2014).
Konsekuensi logis dari premis ini ialah kelompok kelas menengah-atas memiliki kemampuan untuk menghadapi bencana secara lebih baik, sementara kelompok menengah-bawah akan terjebak dalam kerentanan bencana secara akut.
Argumen ini berimplikasi pada pemahaman mengenai resiliensi (ketahanan) bencana. Resiliensi ialah suatu konsep yang merujuk pada kemampuan suatu entitas, individu, atau kelompok dalam melewati masa krisis selama masa bencana dan proses pemulihan serta perbaikan pascabencana (Douglas Paton dan David Johnston, 2017).
Resiliensi biasanya diukur dari dari dua parameter. Pertama ialah masa yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan dan kedua ialah kapasitas untuk menahan beban, tekanan, dan penderitaan selama bencana berlangsung. Parameter yang pertama relatif mudah diukur karena kita bisa melihat durasi proses pemulihan yang diperlukan seorang individu, suatu komunitas, atau masyarakat suatu bangsa untuk kembali ke kehidupan yang normal (bouncing back).
Semakin cepat proses yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan, tingkat resiliensi semakin tinggi. Tingkat resiliensi ini dibentuk modal sosial (social capital) yang memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antarunsur dalam komunitas sehingga mereka mampu pulih dari dampak bencana secara efektif dan cepat.
Parameter yang kedua relatif sulit untuk diukur karena melibatkan berbagai faktor sosiopsikologis yang bersifat inheren dalam perilaku dan cara berpikir seorang individu maupun komunitas. Standarnya, para ilmuwan mengukur parameter ini dari perilaku orang-orang yang terdampak bencana. Tingkat resiliensi dianggap tinggi jika suatu komunitas merespons situasi krisis dengan sikap tenang, perilaku yang stabil, dan cenderung berpikir positif dalam melewati kesulitan yang terjadi.
Mereka mampu melewati goncangan tanpa gejolak sosial yang berarti. Sekali lagi, faktor modal sosial berperan sangat penting dalam menciptakan rasa saling peduli dan empati antara individu dalam suatu komunitas.
Kerentanan versus resiliensi
Dalam teori sosial kebencanaan, tingkat resiliensi selalu dikaitkan dengan tingkat kerentanan. Dalam sudut pandang ini, kondisi struktural yang membentuk kerentanan suatu kelompok bersifat determinan terhadap tingkat resiliensi kelompok tersebut (Katherine Pasteur, 2011). Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya ekonomi dan akses informasi yang dimiliki suatu kelompok, semakin rendah daya tahan dan resiliensi kelompok tersebut dalam melewati masa sulit selama bencana dan proses pemulihan.
Dalam konteks pandemi covid-19, asumsi ini sering dipakai banyak ilmuwan sosial ketika berbicara tentang dampak pandemi, khususnya terhadap kelompok sosial ekonomi kelas bawah. Terdapat dua alasan mengapa cara pandang tentang kerentanan dan struktur sosial menjadi dominan dalam pemahaman mengenai dampak pandemi.
Pertama, berbeda dengan jenis bencana lain yang bersifat kejutan singkat (short-lived shock), seperti gempa bumi dan tsunami. Pandemi ialah suatu bencana yang berjalan secara pelan dan lama (slowburn) dan karenanya menghasilkan dampak sosial ekonomi yang sangat dalam. Dalam situasi ini, kelompok kelas bawah, akan menjadi korban yang paling merasakan konsekuensi dari pandemi, khususnya karena adanya pembatasan sosial.
Kedua, respons terhadap pandemi sangat tergantung pada pemahaman dan persepsi risiko penularan virus korona. Pemahaman dan persepsi risiko ini dibentuk salah satunya oleh tingkat pendidikan. Mayoritas kelompok sosial kelas bawah ialah mereka yang berpendidikan rendah, hal ini melipatgandakan derajat kerentanan kelompok kelas bawah terhadap dampak pandemi.
Pertanyaannya, ‘Apakah kerentanan terhadap pandemi secara otomatis membuat tingkat resiliensi kelompok kelas bawah menjadi rendah?’ Bagi yang percaya bahwa kerentanan ialah fungsi terbalik dari resiliensi, jawabannya iya. Artinya, semakin rentan suatu kelompok terhadap dampak pandemi, semakin rendah tingkat resiliensi kelompok tersebut.
Studi yang kami lakukan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Kerentanan tidak selalu berkorelasi negatif terhadap resiliensi. Kami beranggapan, suatu kelompok bisa saja rentan terhadap dampak pandemi. Tetapi, pada saat yang bersamaan memiliki tingkat resiliensi yang tinggi untuk bertahan dalam situasi darurat. Tulisan ini memberikan bukti empiris dari apa yang kami sebut sebagai fenomena paradoks resiliensi.
Mengukur resiliensi pandemi
Kami melakukan studi dampak pandemi di Indonesia untuk mengukur sejauh mana situasi krisis yang disebabkan wabah covid-19 menghasilkan goncangan sosial ekonomi. Tujuannya melihat diferensiasi goncangan sosial ekonomi di kelompok yang berbeda.
Dalam studi ini, kami menggunakan konsep resiliensi pandemi, yang merujuk pada kapasitas kelompok sosial untuk bertahan dalam situasi pandemi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Kapasitas bertahan kami ukur berdasarkan respons kognitif individu dalam menilai tingkat keparahan dampak pandemi terhadap kehidupan mereka. Resiliensi kami letakkan dalam kerangka pandekatan nonmaterialistis.
Data kami peroleh melalui survei nasional yang melibatkan 997 responden dengan sebaran merata berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lokasi domisili. Survei dilakukan melalui telepon pada akhir Juni hingga awal Juli 2021 ketika gelombang kedua pandemi dengan varian delta sedang menghantam Indonesia. Total ada 24 pertanyaan dalam survei yang kami lakukan.
Data yang masuk kami agregasi ke lima kelompok sosial ekonomi berdasarkan sumber penghasilan, yakni (1) sektor swasta, (2) sektor nonlaba, (3) sektor swausaha, (4) sektor publik, dan (5) sektor informal. Analisis kami terfokus pada sektor informal yang merupakan perwakilan dari kelompok sosial ekonomi kelas bawah.
Dari tingkat pendidikan, kelompok ini didominasi lulusan sekolah dasar (42,03%), lalu lulusan SMA dan sederajat (27,05%), diikuti lulusan SMP dan sederajat (18,36%), lulusan perguruan tinggi (7,73%), dan tidak mengecap pendidikan formal (4,83%). Dari data yang masuk, kami memilih empat bagian yang menjadi konsep pengukuran tingkat resiliensi secara kognitif, yakni (1) kondisi pandemi, (2) kondisi ekonomi, (3) aktivitas sosial, dan (4) persepsi keselamatan.
Kepada memastikan konsistensi keempat variabel ini terhadap konsep resiliensi, kami melakukan uji korelasi dengan menggunakan metode Spearman rho. Hasilnya, seperti yang terlihat di Gambar 1, yakni setiap variabel memiliki korelasi positif yang cukup signifikan satu dengan yang lain.

Selanjutnya, kami memetakan tingkat resiliensi setiap kelompok sosial ekonomi ke jaring laba-laba, seperti yang tertera di Gambar 2. Hasilnya, sektor swasta (biru tua) memiliki jaring yang paling kecil yang berarti mereka merasa terkena dampak pandemi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan kelompok yang lain.

Selanjutnya, sektor nonlaba (abu-abu) dengan tingkat resiliensi yang tidak terlalu jauh lebih besar dari sektor swasta. Sektor swausaha (kuning) dan sektor publik (merah) memiliki jaring yang nyaris berdempet. Artinya, kedua kelompok ini memiliki tingkat resiliensi yang relatif sebanding satu sama lain.
Akhirnya, sektor informal (hijau) ialah kelompok yang memiliki jaring yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ini berarti, kelompok sektor informal yang merupakan perwakilan kelas bawah, ternyata memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi dari kelompok sosial ekonomi lainnya. Hal ini membantah asumsi bahwa kelompok kelas bawah yang rentan, akan cenderung menunjukkan resiliensi yang rendah dalam menghadapi krisis pandemi dengan durasi yang panjang.
Intervensi ini cukup mengejutkan karena penelitian yang sudah ada akan memprediksi orang berada akan lebih mampu bertahan terhadap dampak pandemi. Mereka memiliki uang dan sumber daya yang lain yang bisa mereka andalkan. Yang menarik, walaupun pandemi terjadi di dalam lanskap sosial ekonomi yang memang sudah timpang, justru kaum ekonomi kelas bawah menunjukkan daya tahan yang lebih kuat. Memang ada faktor bantuan sosial yang berperan. Tetapi, efek dari bantuan sosial ini tidak terlalu signifikan mengingat kacau balaunya pemberian bantuan sosial di Indonesia.
Memahami resiliensi
Kami menggunakan skala 7 dalam pengukuran resiliensi. Apabila melihat data secara keseluruhan, tingkat resiliensi memang terlihat rendah. Tetapi, jika kita bandingkan antarkelompok sosial ekonomi, masyarakat kelas bawah yang berada dalam sektor informal relatif lebih unggul dalam hal ketahanan sosial menghadapi dampak pandemi.
Kami menawarkan dua penjelasan tentang paradoks resiliensi ini. Penjelasan pertama, meminjam kerangka modal sosial sebagai fondasi resiliensi yang paling kukuh (Daniel Aldrich, 2012). Dalam perspektif ini, sektor informal memiliki keunikan dalam hal relasi yang terbentuk dalam kelas sosial ini.
Beberapa studi menunjukkan situasi ketidakcukupan materiel masyarakat kelas bawah, justru mendorong terbentuknya ikatan solidaritas dan empati yang menjadi bangunan modal sosial (Stephane Hallegatte dkk, 2016). Penjelasan kedua terkait dengan ignoransi (ketidakpedulian). Pada titik tertentu, ignoransi ialah cara bertahan (coping mechanism) dalam situasi ekstrem (Linsey McGoey, 2016). Ketika beban sosial ekonomi begitu tinggi akibat pandemi, masyarakat kelas bawah mengambil sikap untuk tidak peduli sebagai bentuk respons untuk bertahan.
Tingginya tingkat resiliensi masyarakat kelas bawah bukan berarti bahwa mereka baik-baik saja selama pandemi. Selain itu, juga tidak berarti bahwa pemerintah tidak perlu membantu kelompok sektor informal. Secara materialistis, kita bisa mengukur penderitaan yang mereka alami selama pandemi. Argumen kami terfokus pada kemampuan untuk bertahan dalam masa sulit.
Kita sering mendengar cerita tentang kesulitan yang dihadapi masyarakat secara umum akibat pandemi. Ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang cenderung reaktif dalam menangani pandemi. Tetapi, dalam situasi sulit seperti saat ini, sekelompok masyarakat membangun hubungan sosial baru yang berkembang dengan lebih bermakna. Pada ruang-ruang sosial inilah resiliensi dibangun. Ruang tempat kepedulian, empati, dan solidaritas sesama manusia yang bernasib sama menjadi pengikat sosial yang semakin kukuh. Inilah hikmah sosial dari pandemi.